Kabur di Malam Pernikahan
#Kabur di Malam Pernikahan
“Tak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Semua atas sekenario dan Izin-Nya. Tak terkecuali pertemuanku denganmu.”
(Mutiara Ayu)
Waktu di ponsel menunjukkan jam dua dini hari. Kukira semua orang di dalam rumah, telah terbuai ke alam mimpi masing-masing. Suara riuh para bapak yang sejak tadi bermain kartu di depan rumah tak terdengar lagi. Ini saatnya melancarkan aksi yang semalaman direncanakan.
Kukemas pakaian sepenuhnya ke dalam tas ransel. Kemudian, mematut diri di cermin. Tampak, gadis berkerudung modis terpantul di sana.
Mataku menyapu seluruh ruangan kamar yang telah disulap bak kamar istana kerajaan, tadi siang. Tentu saja fasilitas ratu sehari akan kudapatkan hari ini.
Pak … Mak … maafkan Tiara! Aku mengusap bulir bening yang jatuh tanpa dikomando.
Aku berjalan ke arah jendela kamar, lalu membukanya perlahan. Dengan sigap, aku melewati jendela. Sepatu sport yang dikenakan, cukup membantu usahaku.
***
Butuh waktu lima belas menit untuk sampai di jalanan mulus ini. Jalanan tampak sepi dari kendaraan yang lewat. Biasanya kata tetanggaku, bus jurusan Wado-Bekasi sering lewat jam dua dini hari. Sialnya sekarang sudah jam dua lebih, mungkin saja bus itu sudah berlalu. Alamat harus menunggu bus berikutnya, mana … lama lagi.
Dingin mulai menusuk kulit. Jaket kain yang kukenakan tak mampu mengisolasi hangatnya badan. Aku menepuk jidat, ketika netraku tiba-tiba menagkap lingkaran putih yang sepertinya digambar oleh polisi.
Ya ampun! Aku baru ingat. Kemarin siang, terjadi kecelakaan disini. Pengendara motor tewas di tempat, sedangkan pengendara mobil yang menabraknya dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis.
Seketika bayangan rekaman video yang dikirim temanku lewat grup Whatsapp, sukses membuat bulu kuduk berdiri. Aku menengok ke kiri dan ke kanan. Tak ada satu pun makhluk di sini.
Hiiiy, jadi ngeri, kalau pemuda yang tewas itu tiba-tiba menghantuiku. Lalu mengajakku kawin lari.
“Jangan ganggu … tolong … jangan ganggu, boleh lewat asal jangan menampakkan diri.”
Aku komat-kamit disertai bacaan surat pendek sebisanya. Keringat dingin mulai bercucuran, diiringi tubuhku yang gemetar melawan takut.
Dari kejauhan kulihat sorot lampu mobil. Aku harus ikut mau apapun jenis mobilnya. Daripada terus terperangkap rasa takut.
Cahaya lampu mobil semakin mendekat. Untung akal sehatku masih bekerja. Kurogoh tas ransel bagian depan. Aku hampir saja lupa memakai masker. Bagaimana kalau pengemudi itu mengenaliku? Jadilah aku permaisuri anak juragan kambing.
Kulambaikan tangan ke depan agar mobil itu berhenti. Lampu sein kiri mobil menyala, lalu kendaraan beroda empat itu berhenti tepat di depanku. Aku langsung mengetuk kaca Avanza hitam. Seolah paham, sang pengemudi membuka kaca mobil. Tampak sosok pemuda berkulit putih.
“Maaf A, saya ikut nebeng ya!” Aku memohon dengan nada memelas.
Tanpa menunggu jawaban, aku langsung masuk ke mobil dan duduk di samping pengemudi yang tampak kebingungan.
Aku menarik napas lega, ketika mobil mulai membelah jalanan.
Pengemudi itu melirikku sambil bertanya, “Mbak ini mau ke mana ya?”
“Saya mau ke mana ya?” Tak sadar, aku malah balik bertanya.
Aduh, Tiara bego amat sih kamu!
Memang mau jawab apa? Tujuan mau ke mana pun aku tidak tahu, yang kutahu hanya bagaimana caranya agar tak jadi bersanding di pelaminan bersama lelaki culun itu.
Dia mengerutkan kening. “Lo, kok Mbak nggak tahu mau pergi ke mana?”
Sepertinya pemuda di sampingku itu mulai curiga.
“Maksud saya, Aa teh mau ke mana? Siapa tahu arahnya sama dengan saya,” kilahku.
“Oh … saya mau pulang ke Jakarta, Mbak. Jadi berangkat dini hari, memburu waktu kerja supaya tidak kesiangan,” jelasnya.
“Oh ….” Aku pura-pura menanggapi. Padahal aku tak peduli dia mau ke mana, yang terpenting bagiku adalah jauh dari rumah.
Dia melanjutkan ceritanya. “Saya ke Cilimus ada urusan penting. Biasa sebulan sekali mengikuti pengajian pemuda di sana, sambil titip kado ke oma buat teman saya yang menikah hari ini.”
Uhuk!
Aku tersedak, mendengar ceritanya. Di Cilimus ‘kan hanya aku yang menikah hari ini? Lantas dia siapa? Kok bisa tahu pernikahanku.
“Kok, Mbak melamun? Sebenarnya Mbak mau ke mana?” tanyanya lagi.
“A-aku mau ke … Bekasi. Iya … maksudku Bekasi.” Aku menjawab terbata sambil menyeka peluh yang tiba-tiba luruh ke dahi.
Aku melirik dia yang tampak mengaguk. Mudah-mudahan pria berjaket kulit itu tidak menanyaiku lagi. Soalnya, aku kurang pintar dalam ilmu mengarang.
“Baik, Saya akan bantu Mbak mencari bus jurusan Wado-Bekasi.”
Aku mengaguk. Melirik dia sambil tersenyum tipis.
Setelah mengucapkan terima kasih, aku menyimpan tas ransel di bawah kaki. Lelah yang mendera membuat kantuk menyapa. Aku berusaha melawannya dengan berulangkali mengusap wajah.
Aku merebahkan diri di sandaran jok mobil, senyaman mungkin. Berusaha melawan cemas yang terus menghantui pikiran. Walaupun aku tidak mau dijodohkan, tapi kasih sayangku pada Bapak dan Emak masih sangat besar.
Mengapa sekarang aku jadi keingetan mereka? Ah … seandainya saja Bapak tidak bersihkeras menjodohkanku. Mungkin, semua ini tidak akan terjadi.
Sejujurnya aku tidak sanggup membayangkan bagaimana keadaan Bapak dan Emak begitu mengetahui putri semata wayangnya kabur dari rumah.
Sebenarnya Bapak dan Emak sangat menyayangiku. Aku adalah anak yang sangat dinantikan kehadirannya oleh mereka.
Bapak pernah bercerita kalau Emak sempat mengandung dan melahirkan tiga kali. Namun, kakak-kakakku itu meninggal ketika masih bayi.
Tak ingin mengalami hal serupa, ketika aku dilahirkan Bapak dan Emak sepakat tidak memberiku nama. Mereka hanya memanggilku Oyok asal kata orok bahasa Sunda, yang artinya bayi.
Setelah masuk SD, Emak dan Bapak baru menamaiku Mutiara Ayu, karena tuntutan akta kelahiran.Namun, sampai sekarang mereka tetap memanggilku Oyok.
Aku sudah berusaha membuat panggiilan Tiara untuk diri sendiri. Namun panggilan Oyok tetap akrab di telinga para tetangga dan teman-teman kampungku.
Gegas aku mengusap bulir bening yang tanpa terasa terjatuh. Aku takut pengemudi di sampingku memberondong pertanyaan lagi.
Mobil melaju semakin kencang. Tak ada lagi tanda-tanda suara di antara kami.
***
Suara ketukan yang cukup keras di pintu samping mobil, membuat sulaman mimpiku terputus. Aku mengerjapkan mata yang terasa berat terbuka, lalu menggisiknya agar pandanganku lebih jelas.
“Maaf membuat Mbak kaget, tadi saya sudah berusaha membangunkan, Mbaknya nggak bangun-bangun,” jelasnya sambil tersenyum.
“Kita di mana ya?”
“Kita sudah sampai di Kali Jati. Sekarang sudah memasuki waktu Subuh, Kita salat dulu di situ,” jawabnya sambil menunjuk ke arah mesjid.
Benar saja, tak lama kemudian terdengar kumandang azan. Aku beringsut, keluar dari mobil lalu membuka masker hendak mengusap cairan yang menetes saat tertidur.
“Astaghfirullah, Tiara!!” Pekik pemuda itu.
Aku terperanjat, menatap lekat pria berbadan atletis itu sambil berusaha mengumpulkan memori.
“Abang!! Ini Alif, ‘kan?” Aku mencoba meyakinkan.
Tak salah lagi pemuda itu adalah Alif--teman SD-ku. Dia biasa dipanggil abang oleh oma dan bundanya. Kami teman-temannya memanggil dengan sebutan yang sama.
“Iya, aku Alif!! Tegasnya, “sekarang, ayo aku anterin pulang sebelum semuanya terlambat!”
“Jangan, Bang. Aku mohon.” Reflek, aku memegang tangan Alif dengan erat.
Alif melepaskan tanganku dengan halus.
“Maaf, tadi reflek,” ucapku merasa bersalah.
“Nggak apa-apa yang penting sekarang kita cepat pulang! Orang tua kamu pasti sangat mencemaskanmu.”
“Huwa … aku tidak mau pulang!” Aku menangis agak kencang. Aktingku berhasil menarik salah satu jamaah masjid menghampiri kami.
“Ini ada apa ya A? Kok si Tetehnya sampai nangis,” tanya Jemaah tersebut berempati.
“Teman saya, ngajak pulang terus. Padahal saya mau salat dulu di sini Pa.” Dengan cepat aku menjawab pertanyaannya sambil mengusap air mataku. Sebenarnya bukan air mata buaya, karena aku benar-benar menangis.
Wajah Alif memerah. Dia terlihat salah tingkah.
“Si Tetehnya bener A. Kita salat berjamaah dulu, mumpung belum dimulai.” Ucapan Jemaah tersebut sontak membuatku menahan tawa.
Setelah Jemaah itu berlalu, Alif meninggalkanku tanpa mengucap sepatah kata pun. Aku mengekorinya dari belakang.
Merasa aku ikuti, dia menengok ke belakang.
“kamu mau ke mana?” tanyanya.
“Ya, mau salat lah, geer …,” gerutuku.
Alif berderap kembali menuju masjid.
Setelah melaksanakan salat, aku langsung menuju mobil Alif. Lumayan berdebar juga, takutnya dia sudah berlalu meninggalkanku. Mujur, mobil temanku itu masih terpakir di sana.
Tak lama kemudian, sosok yang ditunggu muncul.
”kamu masih di sini?” ucapnya sambil membuka pintu mobil.
“Iya, emang harusnya di mana?” Aku membuka pintu mobil juga, lalu duduk di sampingnya.
“kirain udah kabur,” sindirnya.
“Aku mohon Bang, tolongin aku!” Aku menangkupkan dua tangan di depan dada.
“Baik, aku akan nolongin kamu dengan mengantarkanmu ke Cilimus,” tegasnya sambil melajukan mobil.
Ternyata Alif tidak main-main. Laju mobilnya menuju ke arah Subang.
“Berhenti di sini! Aku mau turun,” pintaku.
Alif tidak mendengar titahku. Dia tetap saja melajukan mobilnya.
“Kalau tidak berhenti, aku loncat dari sini.” Ancamanku sukses membuat Alif menghentikan mobilnya.
Suara klakson mobil di belakang kami, membuatku urung keluar dari mobil. Tampak Avanza putih itu menghadang mobil Alif.
Jantungku bertalu tidak karuan ketika melihat Bapak dan Mang Kardi keluar dari mobil, disusul Adi--adik sepupuku.
“Kalian mau lari ke mana?” sergah Bapak.
Bapak membuka pintu mobil lalu menarik tanganku.
“Jaga kakakmu ini, Di!" Bapak memberi isyarat kepada Adi.
Aku seperti tahanan tanpa diberogol.
Alif keluar dari mobil. “Maaf Pak, sebenarnya saya….”
“Oh, ini laki-laki yang berani membawa lari pengantin wanita!” potong Bapak.
“Bukan Pa, saya justru akan membawa pulang putri Bapak,” ujar Alif membela diri.
Bapak memukul mobil depan Alif dengan sangat keras.
“Billahi, saya tidak membawa lari putri Bapak!!” Sekali lagi Alif meyakinkan Bapak.
“Bohong kamu!! sergah Bapak, “jangan membawa nama Allah segala, sudah jelas-jelas terbukti masih nyangkal kamu!!”
Rahang Bapak mengeras disertai bunyi gemerutuk gigi. Napasnya tersenggal-senggal sepertinya menahan emosi yang membuncah. Tangannya mengepal kuat membuat urat-urat besar terlihat jelas.
Aku berusaha menenagkan dan meyakinkan Bapak, kalau Alif tidak bersalah. Namun, pria paruh baya itu semakin naik pitam.
“Diam kamu Yok!! Laki-laki ini ‘kan yang mempengaruhi kamu, kabur dari rumah?” selidik Bapak.
“yang salah itu Bapak, Bapak keukeuh menjodohkanku dengan Dadang!!” Aku berbalik menyalahkan Bapak.
“Kamu melawan Bapak, karena laki-laki ini, ‘kan?” Tangan Bapak mencengkram kerah jaket Alif, lalu melayangkan bogem mentah ke wajah temanku itu.
Mang kardi--pamanku, dengan sigap memegang tangan Bapak. “Sabar Kang, Istighfar!"
“Iya, kita selesesaikan dengan kekeluargaan,” timpal Adi ikut menengahi.
Wajah garang Bapak perlahan mengendur. Dia menjatuhkan dirinya ke tanah. Napasnya kembali tersenggal. Kali ini, sepertinya asma Bapak kambuh, dia kesulitan bernapas.
Adi memberikan air botol mineral ke Bapak sambil memijat punggung Bapak.
“Sebaiknya kita pulang sekarang, mumpung masih ada waktu. Sebelum acara akad dimulai,” ujar Adi.
“ Benar Kang,” imbuh Mang Kardi.
Bapak mengaguk lalu melanyangkan pandangan ke arah Alif. “Kamu harus ikut!” desisnya, “jika tidak, saya akan laporkan kamu ke polisi."
“T-tapi Pak, saya …."
“Nak Alif ikut saja, nanti kita selesaikan masalah ini di rumah,” potong Mang Kardi sambil menepuk bahu Alif.
Sekarang aku tak bisa lari lagi. Kakiku serasa terikat oleh tatapan Bapak dan Mang Kardi. Aku menurut masuk ke mobil dengan terpaksa. Air mata terus luruh sepanjang perjalanan pulang. Aku tak bisa membayangkan, sebentar lagi akan bersanding di pelaminan dengan pria pilihan Bapak.
Sekilas tadi netraku mellirik Alif. Tampak dia masuk ke mobilnya ditemani Adi. Sesak menyeruak di dada. Kasihan pria malang itu harus menjadi korban keegoisanku. Hatiku semakin teriris mengingatnya.
***
Sampai di rumah, aku terkejut melihat banyak orang berkerumun. Bukankah hiburan belum dimulai?
Bik Nenih menyambutku dengan wajah cemas. “Alhamdulillah, akhirnya kamu pulang Yok.” Dia menuntunku masuk ke kamar.
Jantungku tiba-tiba berdegup kencang, ketika mendapati Emak berbaring dikerumuni sebagian tetangga.
Aku menghambur, memeluk emak. Tangisku kembali pecah. Bik Nenih bilang Emak pingsan berkali-kali, begitu mengetahui aku kabur dari rumah. Hari ini aku merasa menjadi anak yang paling durhaka.
Bik Nenih memberi isyarat kepada para tetangga supaya keluar kamar.
Aroma kayu putih yang dibalurkan Bik Nenih sukses membuat Emak terbangun. Aku langsung meraih tangan wanita paruh baya itu dan meminta maaf. Emak memelukku dengan erat.
“Alhamdulillah, kamu pulang Yok, Emak mengkhawatirkanmu,” lirih Emak sambil menangkup pipiku.
Aku mengusap air mata Emak yang masih terus berjatuhan. “Emak jangan nangis lagi, Tiara janji akan nurut,” ujarku sungguh-sungguh.
***
Riasan pengantin beserta aksesorisnya kini menempel di badanku. Terdengar decak kagum sang perias melihat pantulanku di cermin.
“Senyum dong Neng, dari tadi kamu cemberut terus,” ucap perias itu sambil memegang daguku.
Aku berusaha menarik bibir ke samping. Namun, tetap saja tidak mampu menyamarkan wajah murung. Bulir bening terus luruh tak mampu ku tahan. Emak berulang kali menyeka air mataku.
“Jangan nangis terus, Yok. Nanti bedaknya luntur,” ujar Emak sambil menitikkan air mata. Mungkin wanita yang melahirkanku itu turut merasakan persaan putrinya.
Terdengar suara riuh dari luar. Mungkin, iring-iringan pengantin pria telah datang bersama dua ekor kambing jantan yang dikalungi emas sesuai yang mereka janjikan. Emak bergegas keluar kamar.
Sekilas mataku menangkap botol berisi obat nyamuk cair.
Bersambung …
Subang, 18 Mei 2020
“Tak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Semua atas sekenario dan Izin-Nya. Tak terkecuali pertemuanku denganmu.”
(Mutiara Ayu)
Waktu di ponsel menunjukkan jam dua dini hari. Kukira semua orang di dalam rumah, telah terbuai ke alam mimpi masing-masing. Suara riuh para bapak yang sejak tadi bermain kartu di depan rumah tak terdengar lagi. Ini saatnya melancarkan aksi yang semalaman direncanakan.
Kukemas pakaian sepenuhnya ke dalam tas ransel. Kemudian, mematut diri di cermin. Tampak, gadis berkerudung modis terpantul di sana.
Mataku menyapu seluruh ruangan kamar yang telah disulap bak kamar istana kerajaan, tadi siang. Tentu saja fasilitas ratu sehari akan kudapatkan hari ini.
Pak … Mak … maafkan Tiara! Aku mengusap bulir bening yang jatuh tanpa dikomando.
Aku berjalan ke arah jendela kamar, lalu membukanya perlahan. Dengan sigap, aku melewati jendela. Sepatu sport yang dikenakan, cukup membantu usahaku.
***
Butuh waktu lima belas menit untuk sampai di jalanan mulus ini. Jalanan tampak sepi dari kendaraan yang lewat. Biasanya kata tetanggaku, bus jurusan Wado-Bekasi sering lewat jam dua dini hari. Sialnya sekarang sudah jam dua lebih, mungkin saja bus itu sudah berlalu. Alamat harus menunggu bus berikutnya, mana … lama lagi.
Dingin mulai menusuk kulit. Jaket kain yang kukenakan tak mampu mengisolasi hangatnya badan. Aku menepuk jidat, ketika netraku tiba-tiba menagkap lingkaran putih yang sepertinya digambar oleh polisi.
Ya ampun! Aku baru ingat. Kemarin siang, terjadi kecelakaan disini. Pengendara motor tewas di tempat, sedangkan pengendara mobil yang menabraknya dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis.
Seketika bayangan rekaman video yang dikirim temanku lewat grup Whatsapp, sukses membuat bulu kuduk berdiri. Aku menengok ke kiri dan ke kanan. Tak ada satu pun makhluk di sini.
Hiiiy, jadi ngeri, kalau pemuda yang tewas itu tiba-tiba menghantuiku. Lalu mengajakku kawin lari.
“Jangan ganggu … tolong … jangan ganggu, boleh lewat asal jangan menampakkan diri.”
Aku komat-kamit disertai bacaan surat pendek sebisanya. Keringat dingin mulai bercucuran, diiringi tubuhku yang gemetar melawan takut.
Dari kejauhan kulihat sorot lampu mobil. Aku harus ikut mau apapun jenis mobilnya. Daripada terus terperangkap rasa takut.
Cahaya lampu mobil semakin mendekat. Untung akal sehatku masih bekerja. Kurogoh tas ransel bagian depan. Aku hampir saja lupa memakai masker. Bagaimana kalau pengemudi itu mengenaliku? Jadilah aku permaisuri anak juragan kambing.
Kulambaikan tangan ke depan agar mobil itu berhenti. Lampu sein kiri mobil menyala, lalu kendaraan beroda empat itu berhenti tepat di depanku. Aku langsung mengetuk kaca Avanza hitam. Seolah paham, sang pengemudi membuka kaca mobil. Tampak sosok pemuda berkulit putih.
“Maaf A, saya ikut nebeng ya!” Aku memohon dengan nada memelas.
Tanpa menunggu jawaban, aku langsung masuk ke mobil dan duduk di samping pengemudi yang tampak kebingungan.
Aku menarik napas lega, ketika mobil mulai membelah jalanan.
Pengemudi itu melirikku sambil bertanya, “Mbak ini mau ke mana ya?”
“Saya mau ke mana ya?” Tak sadar, aku malah balik bertanya.
Aduh, Tiara bego amat sih kamu!
Memang mau jawab apa? Tujuan mau ke mana pun aku tidak tahu, yang kutahu hanya bagaimana caranya agar tak jadi bersanding di pelaminan bersama lelaki culun itu.
Dia mengerutkan kening. “Lo, kok Mbak nggak tahu mau pergi ke mana?”
Sepertinya pemuda di sampingku itu mulai curiga.
“Maksud saya, Aa teh mau ke mana? Siapa tahu arahnya sama dengan saya,” kilahku.
“Oh … saya mau pulang ke Jakarta, Mbak. Jadi berangkat dini hari, memburu waktu kerja supaya tidak kesiangan,” jelasnya.
“Oh ….” Aku pura-pura menanggapi. Padahal aku tak peduli dia mau ke mana, yang terpenting bagiku adalah jauh dari rumah.
Dia melanjutkan ceritanya. “Saya ke Cilimus ada urusan penting. Biasa sebulan sekali mengikuti pengajian pemuda di sana, sambil titip kado ke oma buat teman saya yang menikah hari ini.”
Uhuk!
Aku tersedak, mendengar ceritanya. Di Cilimus ‘kan hanya aku yang menikah hari ini? Lantas dia siapa? Kok bisa tahu pernikahanku.
“Kok, Mbak melamun? Sebenarnya Mbak mau ke mana?” tanyanya lagi.
“A-aku mau ke … Bekasi. Iya … maksudku Bekasi.” Aku menjawab terbata sambil menyeka peluh yang tiba-tiba luruh ke dahi.
Aku melirik dia yang tampak mengaguk. Mudah-mudahan pria berjaket kulit itu tidak menanyaiku lagi. Soalnya, aku kurang pintar dalam ilmu mengarang.
“Baik, Saya akan bantu Mbak mencari bus jurusan Wado-Bekasi.”
Aku mengaguk. Melirik dia sambil tersenyum tipis.
Setelah mengucapkan terima kasih, aku menyimpan tas ransel di bawah kaki. Lelah yang mendera membuat kantuk menyapa. Aku berusaha melawannya dengan berulangkali mengusap wajah.
Aku merebahkan diri di sandaran jok mobil, senyaman mungkin. Berusaha melawan cemas yang terus menghantui pikiran. Walaupun aku tidak mau dijodohkan, tapi kasih sayangku pada Bapak dan Emak masih sangat besar.
Mengapa sekarang aku jadi keingetan mereka? Ah … seandainya saja Bapak tidak bersihkeras menjodohkanku. Mungkin, semua ini tidak akan terjadi.
Sejujurnya aku tidak sanggup membayangkan bagaimana keadaan Bapak dan Emak begitu mengetahui putri semata wayangnya kabur dari rumah.
Sebenarnya Bapak dan Emak sangat menyayangiku. Aku adalah anak yang sangat dinantikan kehadirannya oleh mereka.
Bapak pernah bercerita kalau Emak sempat mengandung dan melahirkan tiga kali. Namun, kakak-kakakku itu meninggal ketika masih bayi.
Tak ingin mengalami hal serupa, ketika aku dilahirkan Bapak dan Emak sepakat tidak memberiku nama. Mereka hanya memanggilku Oyok asal kata orok bahasa Sunda, yang artinya bayi.
Setelah masuk SD, Emak dan Bapak baru menamaiku Mutiara Ayu, karena tuntutan akta kelahiran.Namun, sampai sekarang mereka tetap memanggilku Oyok.
Aku sudah berusaha membuat panggiilan Tiara untuk diri sendiri. Namun panggilan Oyok tetap akrab di telinga para tetangga dan teman-teman kampungku.
Gegas aku mengusap bulir bening yang tanpa terasa terjatuh. Aku takut pengemudi di sampingku memberondong pertanyaan lagi.
Mobil melaju semakin kencang. Tak ada lagi tanda-tanda suara di antara kami.
***
Suara ketukan yang cukup keras di pintu samping mobil, membuat sulaman mimpiku terputus. Aku mengerjapkan mata yang terasa berat terbuka, lalu menggisiknya agar pandanganku lebih jelas.
“Maaf membuat Mbak kaget, tadi saya sudah berusaha membangunkan, Mbaknya nggak bangun-bangun,” jelasnya sambil tersenyum.
“Kita di mana ya?”
“Kita sudah sampai di Kali Jati. Sekarang sudah memasuki waktu Subuh, Kita salat dulu di situ,” jawabnya sambil menunjuk ke arah mesjid.
Benar saja, tak lama kemudian terdengar kumandang azan. Aku beringsut, keluar dari mobil lalu membuka masker hendak mengusap cairan yang menetes saat tertidur.
“Astaghfirullah, Tiara!!” Pekik pemuda itu.
Aku terperanjat, menatap lekat pria berbadan atletis itu sambil berusaha mengumpulkan memori.
“Abang!! Ini Alif, ‘kan?” Aku mencoba meyakinkan.
Tak salah lagi pemuda itu adalah Alif--teman SD-ku. Dia biasa dipanggil abang oleh oma dan bundanya. Kami teman-temannya memanggil dengan sebutan yang sama.
“Iya, aku Alif!! Tegasnya, “sekarang, ayo aku anterin pulang sebelum semuanya terlambat!”
“Jangan, Bang. Aku mohon.” Reflek, aku memegang tangan Alif dengan erat.
Alif melepaskan tanganku dengan halus.
“Maaf, tadi reflek,” ucapku merasa bersalah.
“Nggak apa-apa yang penting sekarang kita cepat pulang! Orang tua kamu pasti sangat mencemaskanmu.”
“Huwa … aku tidak mau pulang!” Aku menangis agak kencang. Aktingku berhasil menarik salah satu jamaah masjid menghampiri kami.
“Ini ada apa ya A? Kok si Tetehnya sampai nangis,” tanya Jemaah tersebut berempati.
“Teman saya, ngajak pulang terus. Padahal saya mau salat dulu di sini Pa.” Dengan cepat aku menjawab pertanyaannya sambil mengusap air mataku. Sebenarnya bukan air mata buaya, karena aku benar-benar menangis.
Wajah Alif memerah. Dia terlihat salah tingkah.
“Si Tetehnya bener A. Kita salat berjamaah dulu, mumpung belum dimulai.” Ucapan Jemaah tersebut sontak membuatku menahan tawa.
Setelah Jemaah itu berlalu, Alif meninggalkanku tanpa mengucap sepatah kata pun. Aku mengekorinya dari belakang.
Merasa aku ikuti, dia menengok ke belakang.
“kamu mau ke mana?” tanyanya.
“Ya, mau salat lah, geer …,” gerutuku.
Alif berderap kembali menuju masjid.
Setelah melaksanakan salat, aku langsung menuju mobil Alif. Lumayan berdebar juga, takutnya dia sudah berlalu meninggalkanku. Mujur, mobil temanku itu masih terpakir di sana.
Tak lama kemudian, sosok yang ditunggu muncul.
”kamu masih di sini?” ucapnya sambil membuka pintu mobil.
“Iya, emang harusnya di mana?” Aku membuka pintu mobil juga, lalu duduk di sampingnya.
“kirain udah kabur,” sindirnya.
“Aku mohon Bang, tolongin aku!” Aku menangkupkan dua tangan di depan dada.
“Baik, aku akan nolongin kamu dengan mengantarkanmu ke Cilimus,” tegasnya sambil melajukan mobil.
Ternyata Alif tidak main-main. Laju mobilnya menuju ke arah Subang.
“Berhenti di sini! Aku mau turun,” pintaku.
Alif tidak mendengar titahku. Dia tetap saja melajukan mobilnya.
“Kalau tidak berhenti, aku loncat dari sini.” Ancamanku sukses membuat Alif menghentikan mobilnya.
Suara klakson mobil di belakang kami, membuatku urung keluar dari mobil. Tampak Avanza putih itu menghadang mobil Alif.
Jantungku bertalu tidak karuan ketika melihat Bapak dan Mang Kardi keluar dari mobil, disusul Adi--adik sepupuku.
“Kalian mau lari ke mana?” sergah Bapak.
Bapak membuka pintu mobil lalu menarik tanganku.
“Jaga kakakmu ini, Di!" Bapak memberi isyarat kepada Adi.
Aku seperti tahanan tanpa diberogol.
Alif keluar dari mobil. “Maaf Pak, sebenarnya saya….”
“Oh, ini laki-laki yang berani membawa lari pengantin wanita!” potong Bapak.
“Bukan Pa, saya justru akan membawa pulang putri Bapak,” ujar Alif membela diri.
Bapak memukul mobil depan Alif dengan sangat keras.
“Billahi, saya tidak membawa lari putri Bapak!!” Sekali lagi Alif meyakinkan Bapak.
“Bohong kamu!! sergah Bapak, “jangan membawa nama Allah segala, sudah jelas-jelas terbukti masih nyangkal kamu!!”
Rahang Bapak mengeras disertai bunyi gemerutuk gigi. Napasnya tersenggal-senggal sepertinya menahan emosi yang membuncah. Tangannya mengepal kuat membuat urat-urat besar terlihat jelas.
Aku berusaha menenagkan dan meyakinkan Bapak, kalau Alif tidak bersalah. Namun, pria paruh baya itu semakin naik pitam.
“Diam kamu Yok!! Laki-laki ini ‘kan yang mempengaruhi kamu, kabur dari rumah?” selidik Bapak.
“yang salah itu Bapak, Bapak keukeuh menjodohkanku dengan Dadang!!” Aku berbalik menyalahkan Bapak.
“Kamu melawan Bapak, karena laki-laki ini, ‘kan?” Tangan Bapak mencengkram kerah jaket Alif, lalu melayangkan bogem mentah ke wajah temanku itu.
Mang kardi--pamanku, dengan sigap memegang tangan Bapak. “Sabar Kang, Istighfar!"
“Iya, kita selesesaikan dengan kekeluargaan,” timpal Adi ikut menengahi.
Wajah garang Bapak perlahan mengendur. Dia menjatuhkan dirinya ke tanah. Napasnya kembali tersenggal. Kali ini, sepertinya asma Bapak kambuh, dia kesulitan bernapas.
Adi memberikan air botol mineral ke Bapak sambil memijat punggung Bapak.
“Sebaiknya kita pulang sekarang, mumpung masih ada waktu. Sebelum acara akad dimulai,” ujar Adi.
“ Benar Kang,” imbuh Mang Kardi.
Bapak mengaguk lalu melanyangkan pandangan ke arah Alif. “Kamu harus ikut!” desisnya, “jika tidak, saya akan laporkan kamu ke polisi."
“T-tapi Pak, saya …."
“Nak Alif ikut saja, nanti kita selesaikan masalah ini di rumah,” potong Mang Kardi sambil menepuk bahu Alif.
Sekarang aku tak bisa lari lagi. Kakiku serasa terikat oleh tatapan Bapak dan Mang Kardi. Aku menurut masuk ke mobil dengan terpaksa. Air mata terus luruh sepanjang perjalanan pulang. Aku tak bisa membayangkan, sebentar lagi akan bersanding di pelaminan dengan pria pilihan Bapak.
Sekilas tadi netraku mellirik Alif. Tampak dia masuk ke mobilnya ditemani Adi. Sesak menyeruak di dada. Kasihan pria malang itu harus menjadi korban keegoisanku. Hatiku semakin teriris mengingatnya.
***
Sampai di rumah, aku terkejut melihat banyak orang berkerumun. Bukankah hiburan belum dimulai?
Bik Nenih menyambutku dengan wajah cemas. “Alhamdulillah, akhirnya kamu pulang Yok.” Dia menuntunku masuk ke kamar.
Jantungku tiba-tiba berdegup kencang, ketika mendapati Emak berbaring dikerumuni sebagian tetangga.
Aku menghambur, memeluk emak. Tangisku kembali pecah. Bik Nenih bilang Emak pingsan berkali-kali, begitu mengetahui aku kabur dari rumah. Hari ini aku merasa menjadi anak yang paling durhaka.
Bik Nenih memberi isyarat kepada para tetangga supaya keluar kamar.
Aroma kayu putih yang dibalurkan Bik Nenih sukses membuat Emak terbangun. Aku langsung meraih tangan wanita paruh baya itu dan meminta maaf. Emak memelukku dengan erat.
“Alhamdulillah, kamu pulang Yok, Emak mengkhawatirkanmu,” lirih Emak sambil menangkup pipiku.
Aku mengusap air mata Emak yang masih terus berjatuhan. “Emak jangan nangis lagi, Tiara janji akan nurut,” ujarku sungguh-sungguh.
***
Riasan pengantin beserta aksesorisnya kini menempel di badanku. Terdengar decak kagum sang perias melihat pantulanku di cermin.
“Senyum dong Neng, dari tadi kamu cemberut terus,” ucap perias itu sambil memegang daguku.
Aku berusaha menarik bibir ke samping. Namun, tetap saja tidak mampu menyamarkan wajah murung. Bulir bening terus luruh tak mampu ku tahan. Emak berulang kali menyeka air mataku.
“Jangan nangis terus, Yok. Nanti bedaknya luntur,” ujar Emak sambil menitikkan air mata. Mungkin wanita yang melahirkanku itu turut merasakan persaan putrinya.
Terdengar suara riuh dari luar. Mungkin, iring-iringan pengantin pria telah datang bersama dua ekor kambing jantan yang dikalungi emas sesuai yang mereka janjikan. Emak bergegas keluar kamar.
Sekilas mataku menangkap botol berisi obat nyamuk cair.
Bersambung …
Subang, 18 Mei 2020


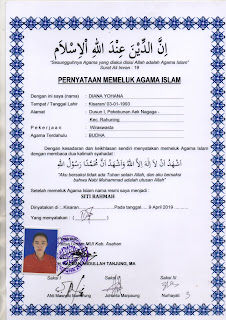

Comments
Post a Comment